
Urupedia-Sebagai anak perempuan sekaligus anak pertama dari dua bersaudara, tidak terbesit untuk merecoki Ibu memasak di dapur atau pun mbuntut ibu untuk melakukan pekerjaannya. Tidak bagi seorang anak yang tinggal di Lereng Kawi itu, ia mencoba pekerjaan yang dilakukan oleh ayah, ikut cari pakan kambing, ngrenceki kayu, mengisi karung dengan kotoran kambing dan metik teh. Saat usia 8 tahun —kurang lebih—usia yang dibilang kecil juga seusia anak-anak sekolah dasar. Sekali diajak muncak, dua kali ketiga kali menjadi candu. Ayah berangkat pagi untuk mencari pakan, menghidupi kambing-kambing yang ada di kandang belakang rumah.
Semua disiapkan, arit, kursi sofa kecil, peninggalan kursi nyinden mendiang mbah putri masih eksis dibawa muncak. Tak hanya untuk duduk, kursi itu multifungsi untuk wadah bekal makanan di bagian kotak bawahnya yang bisa dibuka. pisang, sebungkus nasi dengan kertas minyak beserta lauknya serta sebotol air godogan. Satu jam sangat cukup untuk menyiapkan itu semua beserta tali temali dan uborampe lain.
Sang ayah mulai memanggil anak itu dan menyetater sepeda kuno dengan ban trel yang sedikit suloyo. Jalan-jalan desa disusuri, lambat laun, menuju lereng gunung, sekeliling jalan hanya dipenuhi hijau dedaunan dan semak belukar. Perlahan jalan mulus itu terlewati, berganti jalan-jalan terjal bebatuan yang sangat menantang. Bayangkan jalanan itu tak hanya lurus ibarat penggaris, tapi menanjak sebagaimana papan yang dimiringkan ke tembok sebelah rumah. Tak tahu lagi harus mendetakkan jantung beberapa kali setiap detiknya. Hanya bisa merapal doa agar selamat di sepanjang jalan ngeri itu, mana langit tak cerah alias mendung. Atap langit tertutup pepohonan yang lebat. Akhirnya nafas terengah, sudah sampai pelataran hutan.
Tak cukup di situ, jalan roal coaster masih belum usai. Jika tadi kami bertarung dengan jalan bebatuan sekarang beralih dengan jejalan licin yang sangat dalam, antara jalan dan selokan air tiada bedanya. Motor tua itu mengerahkan segala tenaganya. Aku mendengar nafas ayah yang terengah memberikan kekuatan ekstra untuk mengegas sepeda itu, kami hampir ngguling dan jatuh tertimpa sepeda. Ayah menumpu dengan kaki kanannya, demi anak perempuannya yang begitu manja. Nafasnya tak teratur seperti atlet marathon yang berlari beribu kilo meter. Tapi ini bukan tentang pelarian dari kenyataan, lebih dari itu, melindungi anak perempuannya dari kecelakaan maut.
Suara gas yang nggereng begitu kuat dan keras, jalanan menanjak menjadi problem kami. Akhirnya ’ctak’ rel sepeda tua itu terputus. Kami hampir mundur dalam ketinggian itu. Hampir saja dua nyawa itu melayang, sang ayah dan sosok anak perempuannya. Akhirnya anak itu turun dengan cepat dari sepeda. Ayah itu memerintahkan anaknya untuk lari ke atas lereng, sedangkan ayahnya masih berjuang untuk naik beberapa meter lagi. Namun anak perempuan itu masih melihatnya penuh gelinang air mata. tapi sang ayah memarahinya, agar anak itu segera naik duluan.
Dengan menenteng kursi sinden, anak yang berusia delapan tahun dan tinggi yang tak seberapa itu berlari sekencang mungkin, mencari tempat yang aman. Sambil berteriak dan memanggil “ayah, ayah!” Akhirnya anak itu duduk di bawah pohon yang sudah tumbang, sambil sesekali merapal doa dan melantunkan mantra. Mantra agar tidak disabet oleh lebah hutan yang ganas, dia menyebut lebah itu sebagai tawon bajingan. “nga ta ba ga ma, nya ya ja dha pa, la wa sa ta da, ka ra ca na ha.” Mantra yang diajarkan mendiang neneknya, pemilik kursi empuk yang sedang ia tenteng.
Ia menatap langit, berhasil mendengar suara ayahnya yang mulai dekat. Akhirnya ayah selamat, tapi mereka butuh istirahat sejenak sebelum akhirnya memotong pohon dan ranting kayu untuk keperluan rumah dan pakan kambing. Selama tiga jam berlalu berkutat dengan aungan srigala, kicau burung, dan gemercik air terjun di bawah tebing dua insan itu beristirahat dan memakan bekal. Anak perempuan itu mencari daun teh, tak sengaja ada ulat mati yang masih tertinggal di rantingnya. Si anak kecil tak tahu menahu, bulu-bulu ulat itu menempel dalam pada kulit tangannya yang masih mungil. Anak itu terdiam, menahan panas, gatal dan perih. Beberapa menit kemudian sang ayah datang, “Kenapa, Nduk?” anak itu menyembuyikan tangannya.
Melihat raut anak yang memerah, sang ayah meraih tangannya dan melihat bulu-bulu ulat yang jika bisa dihitung 25 bulu menempel di tangan mungilnya.”Kok iso ki maeng?” (Kok bisa tadi; red?) dengan nada penyesalan. Sang anak terdiam. Sang ayah mengambil ranting daun, dibuatnya sumpit kecil untuk mencabut bulu-bulu ulat di tangan anaknya. Satu demi satu dengan penuh sabar. Sedangkan di cakralawala sana, langit mulai gelap, untung saja tidak turun hujan.
Hari telah larut, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang, jalan mulai gelap, tenaga penghabisan masih tersisa untuk mendorong sepeda tua. Bagaimana sepeda mau berjalan dengan normal? Sementara rantainya putus dan tidak membawa perlengkapan. Al hasil sang ayah menyuruh anak perempuannya naik sepeda, tak tega jika melihat putri sulungnya kelelahan dan payah. Dengan raut penuh yakin, ia tersenyum kepada sang anak “Munggaho Nduk, Bapak tak nyurung sepedah e.” Anak itu tak tahan menyeka air matanya, “Pak kula mandhap.” Kemudian ayahnya menyahut “Numpako sek.”
Anak itu mengalirkan air mata tanpa sepengetahuan sang ayah, sepanjang jalan kenangan, Sang Ayah terengah, beberapa kilo meter jalan bebatuan dengan mata tua yang cukup kabur, disusurinya kegelapan. Demi keselamatan putri kecilnya. “Ayah, kasihmu takkan pernah tergantikan dengan lelaki mana pun,” ia pun menangis di tengah gelapnya malam dan perjuangan sang ayah yang begitu besar.

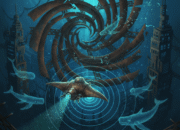





Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.
**mitolyn**
Mitolyn is a carefully developed, plant-based formula created to help support metabolic efficiency and encourage healthy, lasting weight management.