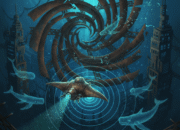Urupedia – Angin berhembus dari arah Selatan, membuat dedaunan kering yang menyatu pada dahan mulai berguguran. Itu tandanya kekuatan bertahan bersama dahan melemah dan ikut bersama hembusan angin yang meneduhkan.
Dari balik jendela tampak seperti musim gugur. Ya, daun-daun berguguran. Hidayat masih saja menetap pada lamunan kosongnya. Banyak santri membawa kitab sembari membicarakan tentang imtihan tsani. Mereka yang berlalu lalang di belakangnya tak digubris. Tak sedikit pun badan Hidayat bangkit dari duduknya. Telinga pun tak mendengar sedikit obrolan mereka.
“Kang, ngaji Tafsir?” Jati menepuk bahu kanan Hidayat.
Hidayat masih saja pada posisi yang sama, hingga tiga kali panggilan Jati tak dihiraukan sedikitpun. Jati mengambil air di kamar mandi, berwadah gayung kuning yang mulai pudar warna aslinya karena tertutup lumut. Gayung yang sudah berumur tua dengan pojokan bawah pecah. Jati menutupi bagian yang pecah dengan tangan kirinya.
“Bismillah. Kang, bangun, bangun. Ngaji Tafsir. Ditunggu, Mbah Yai!”
Percikan demi percikan mampu membangunkan Hidayat dari lamunan panjangnya.
“Ya Allah, hujan. Pakaianku!”
Hidayat sontak terbangun dari duduknya tanpa melihat Jati yang sudah membangunkannya dan berdiri di depannya. Laki-laki berusia dua puluh enam tahun itu berlari tanpa menghiraukan siapapun. Sampai sendal melly merah dengan warna hampir hitam keseluruhan itu tertinggal.
Entah apa yang ada terjadi dengan Hidayat. Tak biasanya santri itu melamun sampai sulit diajak untuk bangun. Jati hanya memperhatikan dari tempat berdirinya dan membiarkannya berlari. Jati sebagai teman dekatnya pun masih terheran-heran dengan keadaan Hidayat.
Lagi-lagi Hidayat berlari kencang menuju loteng tempat penjemuran baju. Satu baris sebelah Barat sendiri dengan beberapa sarung dan baju yang masih tertata dengan rapi.
“Loh, kering. Tadi hujan apa, ya? Apa tadi mimpi, ya? Tapi aku gak tidur kok. Aku masih sadar. Tapi wajahku kok basah.” Hidayat bertanya-tanya tentang apa yang terjadi pada dirinya.
“Ah, ya sudahlah. Yang penting bajuku masih kering. Sabun sudah habis. Kalau sampai basah aku nyuci pakai apa. Sabun sudah habis,” gumam Hidayat.
“Tadi aku yang membangunkan kamu pakai air,” suara dari belakang membuat Hidayat menoleh.
“Lah, kamu Jat. Kenapa sih pakek air segala. Aku kan gak kesurupan.”
“Dari tadi kamu dipanggil not responding. Udah mau ngaji juga. Lah kamu, masih enak-enak bengong. Ingat, pengurus dicontoh anggota!”
“Iya-iya, maaf. Tadi memang aku melamun.”
Jati berjalan meninggalkan Hidayat yang masih diam. Tembok loteng lantai tiga menjadi sandaran Jati untuk menikmati angin Gunung Budheg yang mendapat sebutan gunung purba.
“Kang, sini deh!”
“Apa, Jat?”
“Sampean kenapa to, Kang? Gak biasanya seperti ini.”
“Aku bingung, Jat. Orang tua menyuruhku pulang untuk membantu. Aku punya tanggungan. Dua adikku masih sekolah dan aku harus ikut membiayai mereka sebagai sulung. Besok aku boyong dari sini” guratan sedih raut wajah Hidayat sangat terlihat.
“Kok mendadak? Apa sudah sowan Mbah Yai?”
“Sudah, Jat”
“Apa jawaban beliau?”
“Ya kalau keinginanku seperti ini karena orang tua, Mbah Yai ikut saja. Membolehkan aku boyong.”
Bel pondok berdering tanda waktu salat asar. Mereka menyudahi obrolan singkat dan menuju ke masjid lawang pitu yang terletak di samping ndalem Mbah Yai Muttaqien.
Tas berukuran cukup besar sudah ditenteng Hidayat. Bus Harapan Jaya sudah menanti. Jati di samping Hidayat yang mulai melangkah naik menuju bus.
“Kang, ini ada sedikit uang. Buat bekal saja. Ini tabunganku. Aku ambilkan separuh untuk sampean. Gunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan. Siapa tahu berkembang pesat.” Amplop putih telah berada di tangan Hidayat. Air mata haru juga merasa malu karena merepotkan teman terus bercucuran. Hidayat memeluk Jati yang sudah mau menemani samapi detik itu.
Di dalam bus, Hidayat sudah merencakanan semua yang akan dilakukannya di rumah. Mulai dari membuka usaha yang diselingi dengan berternak. Semua sudah terancang sesuai dengan kondisi rumah yang terakhir dia lihat tiga tahun yang lalu saat perpulangan pondok.
Sambutan haru penuh harap dari orang tua Hidayat membuat semangatnya membara untuk membantu orang tau dan siap membiayai adik-adiknya. Uang pemberian Jati dia gunakan untuk berjualan gorengan di pinggir jalan raya dekat dengan Pasar Wage. Lokasi cukup strategis membuat dagangan pertamanya laku keras. Hari kedua dia memproduksi lebih banyak. Sama seperti hari kemarin, ludes terjual.
Sampai sebulan penghasilan dagangannya melejit sehingga sebagian keuntungan dia gunakan untuk membuka usaha beternak. Bebek menjadi pilihan unggas yang dia ternakkan. Berbeda dengan penjualan gorengan, usaha berternak bebek kali ini Hidayat mendapat musibah. Saat ditinggal belanja membeli pakan, semua bebek digasak maling. Tak ada satupun yang tersisa.
Hari-hari Hidayat menganggur. Tak ada kerjaan juga tak ada yang menyuruh kerja. Semua tanggungan dengan nilai berbeda-beda sudah ada di tangannya. Kini dia harus mencari putaran dana untuk melunasi semua tanggungan.
Seharian penuh dia berjalan mencari putaran dana, namun tak kunjung dapat. Semua kerabat didatangi, tak ada satupun yang memberi. Mencari putaran kesana kemari masih saja hasilnya kosong. Tubuhnya lelah karena terus berjalan. Keluarga Hidayat tidak punya kendaaran sama sekali kecuali sepeda onthel. Itupun digunakan adiknya untuk bersekolah.
“Ya Allah, kok sulit banget nyari kerja,” keluh Hidayat sembari merebahkan badannya di serambi masjid.
Melihat langit-langit masjid membuatnya teringat pada sosok guru yang mengajarinya arti kehidupan. Air matanya menetes. Menyesal ketika teringat dirinya kurang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Setiap hari, waktunya dihabiskan untuk ngopi di kantin. Kalaupun mengaji pasti hanya numpang tidur. Hidayat bertekad untuk sowan pada Mbah Yai Muttaqien.
Terik matahari menyengat kulit. Panasnya membuat siapapun akan malas jika harus keluar rumah dengan cuaca yang sangat panas. Tidak bagi Hidayat. Dia berjalan sejauh lima belas kilo meter untuk sampai jalan raya. Sesampainya di jalan raya, Hidayat menghentikan truk tebu yang mengarah ke Tulungagung.
“Kemana, Mas?”
“Jepun, Pak”
Truk melaju. Syukur saja masih ada tumpangan gratis untuknya. Selama perjalanan Hidayat sama sekali tidak membawa uang saku. Semua modal habis untuk berternak dan kebetulan apesnya semua ternak dicuri maling.
Hidayat turun dari truk. Dia meneruskan jalannya menuju tempatnya menimba ilmu dulu. Hidayat harus berjalan lagi menempuh jarak lima kilo meter. Dia beristirahat hanya untuk sholat dzuhur dan minum air kran di masjid untuk menghilangi dahaga sementara.
Gapura bertuliskan Pondok Pesantren Miftahul Huda berdiri kokoh di depannya. Hidayat memandang sejenak. Malu. Malu harus bertemu kyainya dengan kondisi dirinya seperti itu. Mengingat dulu dia termasuk santri nakal yang belum tuntas namun sudah boyong.
“Loh, iki Hidayat, ya?”
“Injih, Yi.”
Hidayat mencium tangan Mbah Yai Muttaqien. Sebaliknya dengan Mbah Yai Muttaqien memeluk dan membawanya ke ndalem. Dari dulu Mbah Yai Muttaqien tak pernah absen terhadap santrinya. Masyhur dengan sifat tawadhu’nya, pengertiannya, lmannya terhadap santri. Mbah Yai Muttaqien mengajak Hidayat untuk makan terlebih dahulu. Beliau tahu jika Hidayat belum merasakan gumpalan nasi sejak pagi karena persediaan beras sudah menipis.
“Piye, Le?”
“Mbah Yai,” suara gugup dari Hidayat membuat Mbah Yai semakin mendekatkan kursinya agar Hidayat tidak canggung untuk berbicara juga agar orang lain tidak sampai mendengar masalah Hidayat. Mbah Yai sangat pengertian.
“Semenjak saya boyong dari sini saya membuka usaha gorengan. Laku keras, Mbah Yai. Setelah itu saya membuka usaha ternak bebek. Disini apesnya saya, Mbah Yai. Semua bebek hilang dicuri maling saat saya belanja pakan. Dan kini tanggungan sudah banyak, saya sebagai tulang punggung harus melunasi semuanya. Saya sudah berusaha mencari pinjaman kesana kemari namun tak kunjung dapat. Mencari pekerjaan juga sulit, Mbah Yai. Apa yang harus saya lakukan, Mbah Yai?”
Mbah Yai Muttaqien menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. Tampak sangat menikmati setiap cercapan dari butiran kopi juga keluhan santrinya itu. Mbah Yai manggut-manggut memahami keadaan itu.
“Amalan apa yang sudah kamu amalkan sejak boyong dari sini?” tanya Mbah Yai.
Hidayat terkejut. Selama ini Hidayat tak pernah melakukan amalan apapun karena terlalu bersemangat dalam berjualan hingga lupa untuk mengamalkan wirid yang sudah dipelajarinya.
“Ngapunten, Mbah Yai. Saya tidak pernah mengamalkan apapun. Saya sudah sibuk bekerja”
“Le, di pondok sini diwarai wirid opo? Apa yang sudah diajarkan ya itu dilakukan. Eleng, le. Santri ki harus punya wirid tersendiri. Harus punya wirid yang diistiqomahi. Jangan hanya karena kebutuhan dunia kamu melupakan kebutuhan akhirat. Wirid itu gak harus panjang-panjang. Contohnya membaca sholawat setiap hari seribu kali. Apa susah? Kamu meluangkan waktu lima menit untuk ini. Gak begitu menyita waktu kamu. Kalau tidak bisa kamu bisa membagi menjadi dua kali. Atau juga bisa membaca sholawat munajat, nariyah, atau sholawat lainnya. Atau juga istighfar. Ini salah satu amalan yang fadhilahnya membukakan pintu rezeki. Santri utawa alumni santri harus punya wirid. Seperti kamu ini, pulang dari sini juga harus tetap mengamalkan wirid. Kalau santri itu mengamalkan wirid, doa itu gampang mustajab. Sampean tambah dekat dengan Allah, taqarrub ila allah. Jadi dari sekarang amalkan wirid-wirid itu. Sing istiqomah. Insyaallah kalau kamu membuka usaha itu akan barakah, rezeki lumeber. Ojo lali tetep husnudzon marang Gusti Kang nduweni jagat,” dhawuh panjang Mbah Yai Muttaqien.
“Nggih, Mbah Yai. Insyaallah saya amalkan sesuai dhawuh panjenengan. Maturnuwun, Mbah Yai.”
Perlahan hati Hidayat kembali tenang. Adem. Bisa berfikir dengan jernih. Sepulang dari sowan, Hidayat diberi amplop berisi uang satu juta untuk memulai usaha kembali. Hatinya tidak risau. Kini apa yang ada di pikirannya adalah merubah kebiasaan dengan berusaha istiqomah membaca wirid dan merubah mindset buruk tentang sulitnya bekerja.
Editor : Ummi Ulfatus Sy