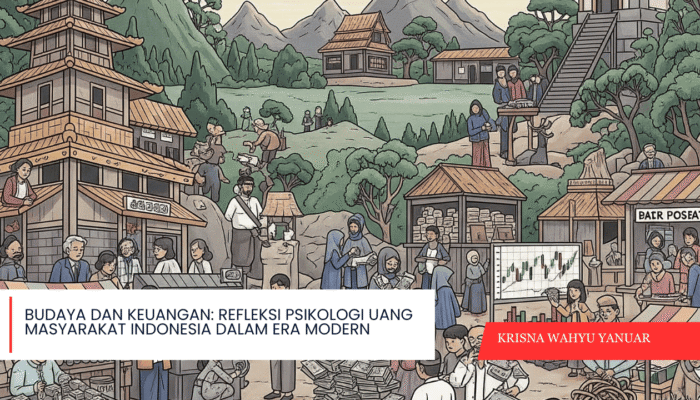
Urupedia.id- Ketika Morgan Housel menerbitkan bukunya The Psychology of Money, ia mengingatkan dunia bahwa uang bukan sekadar angka dalam neraca keuangan, melainkan juga cerminan dari perilaku manusia yang dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, serta nilai-nilai hidup yang diwariskan lintas generasi.
Pandangan ini menjadi sangat relevan bagi Indonesia, sebuah negara yang tidak hanya kaya akan sumber daya, tetapi juga memiliki keragaman budaya yang unik dalam memaknai dan mengelola uang. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, psikologi uang tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya yang mengitarinya.
Indonesia, misalnya, masih berada dalam proses panjang membangun kesadaran literasi keuangan. Data terbaru Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatat bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai 65,43%, sementara tingkat inklusi keuangan berada di 75,02%. Selisih sekitar 9,59 persen ini menunjukkan fenomena menarik: akses dan penggunaan layanan keuangan memang semakin meluas, namun pemahaman mendalam tentang cara mengelolanya belum berbanding lurus dengan angka tersebut.
Artinya, banyak orang Indonesia bisa menggunakan dompet digital atau rekening bank, tetapi belum tentu memahami cara merencanakan investasi atau dana darurat dengan baik. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut Housel: kesuksesan finansial tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui, melainkan bagaimana Anda berperilaku.
Budaya keuangan Indonesia sesungguhnya punya akar historis yang kuat. Sejak lama, masyarakat kita mengenal tradisi menabung melalui bentuk-bentuk lokal seperti arisan, lumbung desa, atau tabungan kolektif di kelompok tani. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencoba menghidupkan kembali nilai itu dengan program Hari Indonesia Menabung serta kampanye literasi keuangan sejak dini.
Di level praktis, menabung masih dipandang sebagai simbol tanggung jawab sekaligus jaminan keamanan finansial. Namun, di sisi lain, perkembangan gaya hidup urban, pengaruh media sosial, serta penetrasi teknologi finansial menciptakan paradoks baru: generasi muda Indonesia cenderung lebih konsumtif, lebih impulsif dalam berbelanja, dan lebih cepat tergoda oleh promo digital ketimbang fokus pada rencana jangka panjang.
Penelitian di Denpasar, Bali, misalnya, menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif terhadap perilaku finansial generasi milenial. Akan tetapi, faktor adopsi fintech payment (dompet digital) dan kecenderungan impulsive buying juga sama kuatnya dalam memengaruhi kebiasaan finansial mereka. Di sinilah psikologi uang bekerja: keputusan keuangan jarang murni rasional. Ia kerap digerakkan oleh emosi, status sosial, dan tekanan lingkungan.
Dalam konteks Indonesia, budaya “gengsi” atau menjaga wajah (face) menjadi salah satu dorongan kuat dalam pola konsumsi. Membeli barang bermerek, nongkrong di kafe populer, atau mengikuti tren fesyen terbaru tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pribadi, tetapi juga simbol eksistensi sosial.
Faktor pengalaman masa kecil pun turut berperan. Mereka yang tumbuh di keluarga dengan keterbatasan ekonomi cenderung lebih berhati-hati dan konservatif dalam mengatur keuangan. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga mapan sering kali lebih berani mengambil risiko dalam investasi. Psikologi uang, dalam hal ini, merupakan hasil dialog panjang antara pengalaman pribadi, nilai budaya, dan dinamika ekonomi.
Maka tidak heran jika generasi Z di Indonesia tumbuh dalam suasana yang kompleks: di satu sisi mereka melek digital dan fasih menggunakan aplikasi keuangan, namun di sisi lain mereka rentan terhadap jebakan paylater, belanja impulsif, dan investasi berisiko tinggi seperti kripto.
Era digital membawa berkah sekaligus tantangan. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan transaksi digital melonjak tajam dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang distandarisasi secara nasional. Kemudahan ini memangkas jarak antara masyarakat dan layanan keuangan.
Namun, kemudahan itu juga membuka ruang bagi perilaku konsumtif yang tak terkendali. Promo cashback, notifikasi flash sale, hingga tren buy now pay later sering kali menjerat pengguna muda untuk bertransaksi tanpa perencanaan matang. Seperti yang diingatkan Housel, pendidikan tinggi tidak menjamin kebijaksanaan finansial jika perilaku sehari-hari tidak terkendali.
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyeimbangkan budaya dan psikologi dalam mengelola keuangan? Jawabannya tentu tidak sederhana, tetapi beberapa jalan bisa ditawarkan. Pertama, integrasi pendidikan finansial dengan nilai budaya lokal perlu diperkuat.
Misalnya, memanfaatkan kearifan tradisi arisan untuk mengajarkan disiplin menabung, atau mengaitkan perencanaan keuangan dengan siklus panen di masyarakat agraris. Kedua, pentingnya kesadaran atas bias emosional dalam pengambilan keputusan: apakah kita membeli sesuatu karena memang kebutuhan, atau hanya sekadar mengikuti tren? Ketiga, adaptasi teknologi harus diarahkan bukan hanya pada kenyamanan transaksi, melainkan juga pada pengelolaan keuangan jangka panjang, misalnya melalui aplikasi budgeting yang membantu generasi muda mengatur pengeluaran.
Lebih dari itu, negara dan lembaga keuangan juga memegang peran krusial. Regulasi terhadap fintech, edukasi keamanan data, dan penyediaan produk keuangan yang ramah pengguna menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah.
Sementara itu, masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan finansial bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa bijak kita mengelolanya. Dalam konteks Indonesia, ini berarti menyeimbangkan antara nilai gotong royong, disiplin menabung, serta adaptasi dengan teknologi modern.
Akhirnya, refleksi psikologi uang ala Housel menjadi semakin kontekstual ketika dipadukan dengan realitas Indonesia. Uang bukan sekadar alat tukar, ia adalah cermin budaya sekaligus arena pergulatan emosi manusia.
Bila kita mampu menyadari pengaruh budaya dan psikologi dalam setiap keputusan finansial, maka perjalanan menuju kesejahteraan tidak lagi hanya soal angka di rekening, tetapi juga soal harmoni antara nilai, perilaku, dan masa depan yang kita cita-citakan bersama.
Daftar Pustaka
- Antara. (2025, Februari 7). OJK latih petugas survei literasi keuangan 2025 di Bali. Antara News. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4520791/ojk-latih-petugas-survei-literasi-keuangan-2025-di-bali
- Bank Indonesia. (2024). Sistem Pembayaran Indonesia (SPI): Statistik Transaksi QRIS. BI.go.id. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/spip/default.aspx
- Housel, M. (2020). The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happiness. Harriman House.
- Jurnal Ilmiah Cendekia Nusantara. (2024). Analisis literasi keuangan dan minat penggunaan dompet digital pada mahasiswa. JICN, 4(2), 150–162. Diakses dari https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/605/683/3344
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025, Agustus 14). Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2025. OJK.go.id. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Hari-Indonesia-Menabung-dan-Bulan-Literasi-Keuangan-2025.aspx
- Putra, I. W., & Lestari, N. P. (2024). Perilaku keuangan generasi milenial di Kota Denpasar: Pengaruh literasi keuangan, adopsi fintech payment, impulsive buying, dan financial self-efficacy. ResearchGate. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/389974941
- Suartini, N. N., & Yulianti, A. A. (2024). Analisis literasi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap keputusan investasi generasi Z di Denpasar. Jurnal Maneksi, 13(1), 102–115. Politeknik Negeri Manado. Diakses dari https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/2551/1268
- Widya, A. P., & Sari, M. K. (2023). Pengaruh literasi keuangan, financial self-efficacy, dan locus of control terhadap keputusan investasi masyarakat Kota Denpasar. Jurnal EMAS, 7(2), 45–59. Universitas Mahasaraswati. Diakses dari https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/emas/article/view/11328






