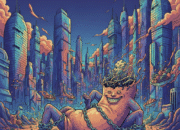Urupedia.id- Belakangan ini, berbagai peristiwa kembali menyuguhkan kenyataan pahit tentang nasib anak-anak.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hingga hari ini mereka masih berada dalam kondisi yang jauh dari rasa aman dan perlindungan.
Pemberitaan media memperlihatkan bahwa kelompok usia paling rentan ini bukan hanya hidup dalam ketidakamanan material dan psikologis, tetapi juga kerap menjadi sasaran eksploitasi yang keji oleh orang dewasa.
Kasus seorang anak berusia sepuluh tahun, siswa kelas empat sekolah dasar, yang meninggal akibat bunuh diri, menjadi salah satu peristiwa paling menyesakkan.
Tragedi ini menggambarkan tekanan hidup luar biasa yang dialami seorang anak yang tumbuh dalam keluarga dengan kemiskinan ekstrem.
Berdasarkan keterangan aparat kepolisian, sebelum kejadian tersebut ia sempat meminta uang untuk membeli buku dan alat tulis, namun permintaan itu ditolak oleh ibunya. Terdapat pula informasi bahwa anak tersebut sering mengeluhkan rasa lapar.
Peristiwa ini dengan jelas memperlihatkan bagaimana ketertekanan hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dapat berdampak sangat serius terhadap kondisi psikologis anak.
Negara sebenarnya telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Namun dalam praktiknya, tidak semua keluarga yang membutuhkan dapat mengakses program tersebut. Persoalan pendataan, kendala administratif, serta ketidaktepatan sasaran kerap menjadi hambatan utama.
Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, merupakan salah satu program perlindungan sosial yang bertujuan menjamin pemenuhan gizi, kesehatan, serta pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Sayangnya, berbagai kendala struktural membuat manfaatnya belum dirasakan secara merata. Isu salah sasaran bantuan sosial pun terus menjadi perbincangan publik.
Kemiskinan merupakan kondisi yang sangat merusak proses tumbuh kembang anak. Fakta bahwa kemiskinan ekstrem masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Ketimpangan sosial ini, salah satunya, lahir dari kebijakan negara yang belum sepenuhnya menghadirkan keadilan ekonomi.
Kekayaan masih terkonsentrasi pada segelintir elite, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam keterbatasan.
Kekayaan alam yang melimpah tidak sepenuhnya dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan justru lebih banyak mengalir ke kepentingan para pemilik modal, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh praktik korupsi yang masih mengakar. Uang negara yang bersumber dari pajak rakyat dan hasil pengelolaan sumber daya alam kerap diselewengkan oleh para pejabat.
Akibat dari pengelolaan negara yang buruk ini, anak cucu kitalah yang pada akhirnya harus menanggung dampaknya: lingkungan yang rusak, ketimpangan sosial yang makin tajam, dan menyusutnya kesempatan hidup yang layak.
Nasib buruk yang dialami anak-anak tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan dan pemiskinan struktural. Fenomena lain yang tak kalah mengerikan adalah eksploitasi seksual terhadap anak.
Belakangan ini, media internasional kembali menyoroti terbukanya dokumen persidangan yang dikenal sebagai Epstein Files.
Dokumen tersebut mengungkap praktik perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak perempuan yang melibatkan jaringan orang-orang kaya dan berpengaruh dari berbagai negara.
Jeffrey Epstein, dengan bantuan Ghislaine Maxwell, merekrut dan memperdagangkan gadis-gadis di bawah umur untuk kepentingan seksual kalangan elite global. Pada Juni 2022, Maxwell dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas perannya dalam kejahatan tersebut.
Fakta persidangan menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun mereka mengidentifikasi, membujuk, dan memanipulasi para korban, lalu membawa mereka ke berbagai lokasi mewah milik Epstein di New York, Florida, New Mexico, dan tempat lainnya, dengan kedok liburan atau perawatan pribadi.
Perdagangan manusia, termasuk perdagangan anak, masih terus terjadi dengan berbagai modus. Penculikan, penipuan, hingga eksploitasi lintas negara menjadi praktik kejahatan yang berulang.
Anak-anak perempuan kerap dijadikan komoditas dalam industri kejahatan seksual global, di mana tubuh mereka diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang.
Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa anak-anak kita belum sepenuhnya aman. Di lingkungan rumah, mereka dapat menjadi korban kondisi keluarga yang tidak sehat.
Di sekolah pun situasinya tidak selalu lebih baik. Kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia.
Di negara maju seperti Amerika Serikat (AS) pun, anak-anak perempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya sendiri.
Pada September 2023, seorang pria bernama Jesus Concepcion di AS mengaku bersalah atas sepuluh dakwaan pelecehan seksual terhadap lima korban di bawah umur yang merupakan muridnya.
Usia korban termuda saat kejadian adalah 12 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah sekolah swasta publik di Bronx, New York. Pada September 2024, Concepcion dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun.
Tindak kejahatan tersebut dilakukan dalam rentang waktu 2000 hingga 2007. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai pendidik, pelaku membujuk dan memanipulasi para murid dengan membuat mereka percaya bahwa mereka memiliki hubungan romantis.
Ia melakukan tindakan seksual terhadap empat korban di berbagai lokasi, termasuk di lingkungan sekolah, sebuah motel di New Jersey, serta di rumah pribadinya.
Di belahan dunia lain, anak-anak juga menjadi korban eksploitasi dalam situasi perang dan konflik bersenjata. Mereka bukan hanya terdampak ketika wilayah tempat tinggalnya dibombardir, seperti yang dialami anak-anak di Afghanistan dan Irak saat invasi Amerika Serikat pada awal abad ini, tetapi juga dalam berbagai konflik bersenjata di wilayah lain.
Dalam kondisi perang, anak-anak bahkan kerap dilibatkan sebagai bagian dari pasukan tempur. Di Amerika Latin pada masa kediktatoran, misalnya, mereka menjadi korban kekerasan negara sekaligus direkrut secara paksa untuk menghadapi kelompok perlawanan, sebagaimana pernah terjadi di Ekuador.
Hal serupa juga dialami anak-anak di Jalur Gaza, yang sejak lahir telah hidup di tengah konflik berkepanjangan.
Anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam suasana damai, memiliki kesempatan bermain dan belajar secara menyenangkan, justru harus menjalani kehidupan yang dipenuhi kebencian dan kekerasan.
Anak-anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan sejatinya membutuhkan ruang dan waktu untuk berkembang secara wajar.
Namun perang merampas kesempatan itu, sehingga mereka kehilangan peluang untuk memahami dunia secara utuh. Gambaran ini dapat dilihat dalam film Blood Diamond yang dibintangi Leonardo DiCaprio.
Dalam film tersebut, seorang anak bernama Dia terpisah dari kedua orang tuanya setelah diculik oleh kelompok bersenjata. Ia sebelumnya bercita-cita menjadi dokter, sesuai harapan ayahnya. Namun di kamp penculikan, bersama anak-anak lain, ia dilatih untuk membunuh dan didoktrin dengan kekerasan.
Latihan pertamanya adalah menembak seseorang yang masih hidup tanpa mengetahui siapa korbannya. Seiring waktu, Dia tumbuh menjadi remaja yang terlatih melakukan kekerasan demi perebutan kekuasaan, dengan tugas awal merebut wilayah pertambangan berlian di Sierra Leone, Afrika.
Situasi dunia saat ini menunjukkan potensi berlanjutnya penderitaan anak-anak.
Krisis ekonomi akibat sistem kapitalisme global, disertai persaingan antarkekuatan ekonomi dunia yang berisiko memicu konflik berskala besar, semakin memperburuk keadaan.
Krisis ekonomi yang tajam sering kali melemahkan daya beli keluarga, meningkatkan pengangguran, serta ditandai dengan kebangkrutan perusahaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja.
Dalam kondisi seperti ini, anak-anak kembali menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Oleh: Nurani Soyomukti
Editor: David Yogi