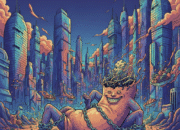Urupedia.id- Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005, guru adalah pendidik profesional. Mereka memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Penyebutan “Pendidik Profesional” bukan sekadar label, melainkan sebuah tanggung jawab hukum dan moral yang sangat besar.
Profesionalisme seorang guru menuntut adanya integritas yang utuh, di mana kompetensi sosial dan kepribadian menjadi fondasi utama dalam berinteraksi di lingkungan sekolah terutama saat mengajar dan mendidik.
Artinya, predikat profesional harus tecermin dalam kematangan sikap, kearifan dalam bertindak, serta kesantunan dalam bertutur kata.
Seorang pendidik yang profesional memikul beban moral untuk menjadi teladan hidup bagi lingkungan sekitarnya.
Hal ini sejalan dengan pesan Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, bahwa guru adalah sosok yang harus mampu menerapkan semboyan Ing Ngarsa Sung Tuladha. Artinya, di depan ia harus menjadi teladan.
Keteladanan ini tidak hanya berlaku di hadapan peserta didik di dalam kelas, tetapi juga melalui perilaku sehari-hari baik itu di ruang guru.
Seorang pendidik adalah cermin hidup, setiap tutur katanya adalah pelajaran, dan setiap sikapnya adalah kurikulum yang berjalan.
Namun sayangnya, realita di lapangan sering kali menunjukkan celah yang lebar antara gelar dan perilaku.
Dunia pendidikan kita sedang berlomba mengejar predikat profesional. Gelar Gr. (Guru Profesional) kini banyak tersemat di nama para pendidik, sebuah bukti kompetensi yang diakui negara.
Namun, ada satu hal yang tidak bisa diukur oleh lembar sertifikasi, yakni pengutaman adab dan etika dalam berinteraksi sesama.
Terkadang disela-sela jam istirahat, atau di ruang guru, terjadi sebuah fenomena miris yang dianggap normal seperti “boddy shaming” yang dibalut dengan candaan, meluncur begitu saja diikuti tawa ringan.
Bagi si pelontar, itu mungkin hanya “basa-basi”. Namun bagi si penerima, kalimat itu bisa jadi adalah belati yang menusuk luka lama. Luka yang Tak Terlihat
Kita tidak pernah tahu beban apa yang dibawa seseorang di punggungnya. Bagi banyak orang, komentar negatif tentang fisik adalah pemicu trauma masa kecil.
Banyak anak yang tumbuh besar dengan perundungan dari orang-orang dewasa di sekitarnya bahkan dari keluarga sendiri.
Ketika mereka dewasa dan masuk ke lingkungan kerja profesional, mereka berharap telah menemukan “ruang aman”.
Sangat ironis ketika seorang guru yang telah tersertifikasi profesional justru menjadi pelaku perundungan verbal.
Mengomentari berat badan atau bentuk tubuh rekan kerja bukan hanya tindakan tidak sopan, tapi juga menunjukkan rendahnya kecerdasan emosional.
Tubuh seseorang, baik itu kurus maupun berisi bukanlah properti publik yang boleh dikomentari demi mencairkan suasana.
Bukan “Baper”, Tapi Batasan. Sering kali korban perundungan baik itu di ruang guru dicap “baperan” atau terlalu sensitif jika mereka merasa tersinggung.
Padahal, masalahnya bukan pada sensitivitas korban, melainkan pada ketidaktahuan pelaku dalam menjaga batasan.
Sebagai pendidik yang “digugu dan ditiru”, lisan kita adalah kurikulum yang paling nyata bagi murid-murid kita. Jika kita menormalisasi perundungan fisik di kantor (sekolah) maupun di tempat lain, maka secara tidak langsung kita sedang melegalkan bullying di lingkungan sekolah.
Sebelum kita mendidik siswa, didiklah lisan kita terlebih dahulu. Karena sebuah “candaan” hanya disebut lucu jika semua orang tertawa. Jika ada yang tersakiti, itu bukan candaan itu adalah penghinaan.
Bullying adalah bahasa yang paling genosida.
Ali bin Abi Thalib pernah berkata yakni, kelak kau akan mengerti, bahwa menahan agar orang lain tak tersinggung karena lisanmu itu jauh lebih mulia dari pada mengutarakan isi hatimu.
Oleh: Widya Ishak, Ternate