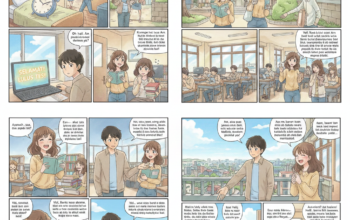Santri itu bernama Zulfan. Bukan siapa-siapa, bahkan bukan juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat RT. Bukan juga penghafal kitab Alfiyah, apalagi ahli sharaf yang bisa menjelaskan perubahan fi’il seperti politisi mengubah janji. Zulfan hanyalah satu dari dua ratus santri di Pesantren Al-Mubarak, pesantren yang punya dua aula besar: satu untuk ngaji, satu lagi untuk podcast.
Kyai-nya bernama Kyai Romli bin Ma’rufin bin Viraluddin, atau lebih dikenal di TikTok sebagai @kyai_visioner. Pengikutnya dua juta, lebih banyak dari jumlah jemaah shalat subuh di seluruh kota tempat pesantren itu berdiri. Beliau ulama—katanya—juga selebriti, dan sejak dua tahun terakhir, politisi. Partainya berubah sesuai arah angin, tapi katanya demi maslahat umat. Dan umat, sebagaimana biasa, manut saja seperti anak ayam kehilangan induk, asal dikasih sembako dan selfie bareng.
Zulfan punya satu keistimewaan: tidak punya filter. Mulutnya polos, pikirannya seperti air wudhu—mengalir, menyucikan, tapi dingin kalau disiram ke kepala orang yang sedang main gawai.
Suatu pagi, selepas subuh yang diimami rekaman suara Kyai Romli (karena beliau sedang ada acara sarungan bareng artis ibu kota di hotel bintang lima), Zulfan memberanikan diri bertanya pada Ustadz Safrul, guru ngaji muda yang diam-diam juga sudah frustrasi.
“Ustadz,” tanya Zulfan polos, “apa bedanya ngaji sama live Instagram?”
Ustadz Safrul menahan batuk. Ia tahu, pertanyaan itu seperti menggugat fondasi pesantren modern ini.
“Ngaji itu… mencari ilmu lillah. Kalau live Instagram… ya, mencari viewer billah.”
Zulfan mengangguk, tapi malamnya ia menulis di mading santri sebuah puisi berjudul “Kyai yang Rindu Followers”. Isinya begini:
Dulu ulama didatangi, bukan mendatangi.
Kini ulama menunggu like, bukan ilham Ilahi. Dulu ceramah bersahaja, kini pakai ring light tiga. Kapan kitab kuning diulas, bukan cuma endorse pasta gigi rasa miswak?
Mading itu bertahan 12 menit sebelum dicopot oleh staf IT pesantren.
Besoknya Zulfan dipanggil ke kantor Kyai Romli. Ruangan megah ber-AC, rak kitab bersusun rapi, walau sebagian masih dibungkus plastik.
“Santri kecil,” kata Kyai Romli dengan suara lembut yang biasa ia pakai saat jadi bintang tamu di talkshow Ramadan. “Kamu tahu tidak, zaman sekarang ini dakwah harus kreatif.”
Zulfan menjawab tenang.
“Betul, Kyai. Tapi kenapa lebih banyak kreatifnya daripada dakwahnya?”
Kyai Romli terdiam. Kamera CCTV merekam semuanya. Mungkin besok akan dijadikan konten, diberi judul: “Santri Nakal Dibina dengan Hikmah oleh Kyai Kekinian.”
“Dakwah butuh panggung, nak,” lanjut sang Kyai. “Umat sekarang tidak akan dengar suara kebenaran kalau tidak ada efek background musik dan transisi yang halus.”
“Lalu, Kitab Ihya’ Ulumuddin di mana, Kyai?” tanya Zulfan. “Kenapa sekarang yang dihapal justru rating, subscriber, dan algoritma?”
“Nak, kamu terlalu lugu. Ini zaman post-truth, bukan pesantren kuno di kampungmu dulu.”
Zulfan nyengir.
“Tapi Rasulullah tidak pernah endorse kurma dari brand tertentu, Kyai.”
Beberapa hari setelah percakapan itu, Zulfan mendapati bahwa namanya tidak lagi tercantum di daftar santri aktif. Di e-brosur pesantren edisi bulan ini, wajahnya hilang digantikan foto Kyai Romli sedang duduk bersama tiga selebriti hijrah, dua di antaranya baru saja cerai.
Zulfan tak kecewa. Ia pulang ke desanya, membawa satu koper berisi dua kitab kuning, satu buku puisi Rendra, dan satu baju koko yang masih utuh karena selama ini tidak sempat dipakai: acara ngaji lebih sering disuruh pakai batik sponsor.
Di kampung, Zulfan mulai mengajar anak-anak ngaji di surau kecil. Ia tidak punya kamera, tidak ada mic, tidak ada ringlight. Tapi anak-anak datang. Tidak ada iklan, tidak ada gimmick. Tapi ayah-ibu mereka mempercayainya. Bukan karena followers-nya banyak, tapi karena wajahnya jujur.
Enam bulan kemudian, viral sebuah video. Isinya: potongan ceramah Kyai Romli yang sedang marah-marah karena netizen menyebutnya “kyai endorse”.
“Mereka itu iri!” kata Kyai dalam video itu. “Saya ini ulama yang melek zaman! Santri harus bisa jadi artis, jadi influencer! Ini bagian dari dakwah 5.0!”
Netizen pun tertawa. Meme-meme bermunculan. Salah satunya gambar Kyai Romli berdiri di antara dua billboard: satu bergambar kitab, satu lagi iklan sabun muka. Caption-nya: “Antara Nur dan Sponsor.”
Di sisi lain, Zulfan tetap di kampung. Ia tidak tahu dirinya mulai dibicarakan sebagai “santri yang tidak viral tapi menyejukkan.” Ia hanya tahu bahwa tiap malam, suraunya semakin ramai. Bahkan ada beberapa mahasiswa dari kota yang datang untuk belajar tafsir.
Satu dari mereka bertanya:
“Gus, kenapa sampean nggak ikut-ikutan bikin konten religi di TikTok? Kan bisa terkenal…”
Zulfan menjawab sambil tersenyum:
“Kalau ilmu saya masih dangkal, kontennya cuma akan jadi lucu-lucuan. Tapi kalau saya ikhlas, meski diam pun mungkin bisa jadi dakwah.”
Mahasiswa itu terdiam. Lalu mengambil kitab. Lalu duduk.
Suatu hari, televisi nasional mengundang Zulfan untuk hadir dalam program debat: “Pesantren Kekinian vs Pesantren Konvensional: Mana Lebih Islami?”
Zulfan menolak. Ia berkata:
“Saya tidak mau Islam dijadikan bahan adu argumen sambil diselingi iklan es krim.”
Kini, nama Kyai Romli mulai pudar. Terlalu banyak kontroversi, terlalu sering berpindah posisi politik, terlalu sering tampil tanpa substansi. Tapi ia tidak marah. Ia hanya menyuruh tim kreatifnya membuat konten nostalgia: “Kyai yang Dulu Pernah Viral.”
Sementara itu, Zulfan—yang tak pernah menginginkan panggung—pelan-pelan dikenal sebagai “kyai muda kampung” yang menyejukkan. Tidak viral, tapi mengakar. Tidak lucu, tapi menumbuhkan. Ia menjadi contoh bahwa kadang, keheningan lebih berwibawa daripada ribuan komentar.
Dan di suatu mading sederhana, tulisan ini terpampang:
Yang diam tak selalu kalah, kadang ia sedang mengaji lebih dalam. Yang tidak tampil, bukan berarti redup, tapi sedang menyalakan lilin dari dalam dada umat.