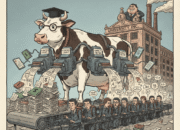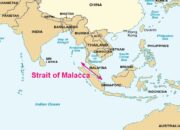“Filsafat, ngeri ya!” ucap seorang karib yang tinggal di desa saya. Memang demikianlah bagaimana cara pandang masyarakat secara umum (common sense) memahami apa itu filsafat. Padahal, sedari sekolah dasar kita telah dibekali pemahaman sederhana atas nilai-nilai filosofis atas suatu hal, semacam falsafah Pancasila, falsafat Jawa atau falsafah bangsa. Lalu mengapa kita “merasa” jauh dari filsafat? Dan menganggapnya hanya dipahami oleh para dukun, orang pintar dan para pakar “kelangitan” lainnya.
Uniknya, berimbas dari meredupnya tradisi mendongeng di ruang-ruang pendidikan kita saat ini, lunturnya sastra dalam penanaman konstruk moral mengakibatkan generasi kita kehilangan khazanah lokal atas identitas primordial, semacam siapa kita, berasal dari mana dan akan hidup seperti apa.
Ambilah contoh, generasi saat ini akan sukar memahami yang “astral,” ketika di tanya perihal siapa yang membantu Bandung Bondowoso dalam suksesi pembangunan Candi Prambanan. Pastilah mereka akan menjawab “Minion… Doraemon… Naruto.” Fakta ini memperlihatkan bagaimana cara kerja matinya sastra, filsafat, sejarah dan folklore dalam narasi nalar masyarakat kita.
Filsafat bukan barang antik, bukan keilmuan yang berat atau bahkan cara kerja sebuah nalar yang rumit. Digali dari etimologinya, filsafat “hanya” berasal bahasa Yunani, dari kata “Philia” dan “Sophia.” Philia sederhananya bermakna “berkarib, mencintai atau berteman,” sedangkan Sophia berarti “kebijaksanaan.”
Mudahnya, filsafat adalah sikap mencintai kebijaksanaan. Hal ini selaras, seperi yang ditegaskan F. Budi Hardiman bahwa filsafat adalah dambaan. Dambaan bagi mereka yang terus mencari, meneliti dan mencintai kebajikan. Berfilsafat juga berarti tindakan mencintai (to loving) dan memahai (to meaning) apapun, entah tuhan, sesama manusia, alam semesta atau angka-angka yang dipuja oleh generasi kita saat ini.
Berfilsafat menghendaki akan adanya keberanian, tegas Ludwig Wittgenstein. Keberanian untuk mendalami suatu hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia pada umumnya. Contohnya, Sokrates memiliki satu diktum: “Apakah kita hidup untuk makan, atau makan untuk hidup?” Pola pikirin semacam ini enggan dipikirian lebih dalam oleh sebagian orang.
Martin Heidegger bahkan lebih dalam, ia bertanya: “Penyentak apa yang paling membuat manusia berpikir?” jawabnya “adalah ketidakberpikiran itu sendiri.” Kita telah memahami makna mendasar dari filsafat, dan inilah saat paling tepat kita menyadarinya.
Memang benar bahwa berfilsafat juga memerlukan unsur-unsur primer. Semisal kita harus radikal, kritis, analitis dan sistematis. Kord-kord (tali-tali, red) ini memperlihatkan capaian orang dalam berfilsafat akan selalu beragam. Ada yang menggunakan logika murni, intuisi, pembuktian empiris-observasi dan lain sebagainya.
Varian pendekatan ini menjelaskan kerumitan filsafat yang sebenarnya tidak rumit. Nyatanya, jika ditarik dalam elemen mendasarnya, filsafat terbagi dalam tiga rumpun besar: aksiologi, ontologi dan epistemologi
Aksiologi mengukur (value) nilai dan etika dari suatu hal. Bertujuan mencari pusara maksa. Berbeda dari itu, ontoligi menjerumuskan kita pada pertanyaan: apa itu ada? Bagaimana bisa ada? Dari mana ada?, ontologi mempertanyakan hal esensial dari seuatu keberadaan.
Dan yang terakhir lebih intim, epistemologi berlaku untuk menegur suatu temuan: apa itu pengetahuan? Bagaimana sesuatu itu dapat dikatakan sebagai pengetahuan?. Berbagai pranata ini membingkai utuh hingga dapat dikatakan sebagai filsafat.
Generasi saat ini, Milenial, mungkin sulit mengobservasi dirinya sendiri. Efek dominan dari “candu” teknologi, lunturnya tradisi dialog, pendidikan yang hanya berpaku pada angka dan problem-problem substansial lainnya telah memperkeruh generasi ini. Tak dapat dipungkiri, baik-buruknya teknologi dan zaman kontemporer yang kini riuh diperbincangkan, merubah paradigma manusianya akan hubungannya dengan tuhan, alam dan sesama.
Tak salah dan tak benar, instannya pengetahuan yang mudah di unduh, malah membuat gaduh. Saya pribadi yang bergiga-giga mengoleksi file buku elektronik, belum tentu membacanya secara tematik. Faktanya malah saya jauh dari tradisi membaca.
Kita dimabukkan oleh hiburan lain, semacam film, anime, Tiktok, Instagram dan platform sosial media lainnya. Semisal menyelam di lautan, kita berencana mencari ikan “pengetahuan,” kita malah tersangkut atau bahkan mendapatkan sampah, jala nelayan atau limbah tambang.
Tetapi jangan minder dulu, se-absurd mungkin kita berfilsafat di era saat ini, sebenarnya kita masih mampu, nisbi dan mungkin. Jangan salah, generasi ini gampang peka kok! Selain dari kecenderungan yang saya sebutkan di atas, generasi milenial masih memiliki suatu mental yang keren, yakni “adaptif.”
Selain mudah mencerna informasi apapun, jika ditarik ke ranah yang lebih luas, generasi milenial juga mampu adaptif dalam berpengetahuan, tinggal bagaimana pondasi berpikir dan penanaman “kesenangan atas pengetahuan” (pleasure of knowledge) wajib di rakit.
Mengembalikan materi filsafat di ruang pendidikan formal, memaksimalkan tradisi dialog (virtual/offline) dan kita tahu, masyarakat kita adalah masyarakat gotong royong, modal menarik inilah yang bisa mengembalikan generasi ini kepada jalan yang benar. Benar dalam berpikir, benar dalam beragama, benar dalam bernegara, benar dalam hubungan antar memanusia dan benar-benar memahami dirinya sendiri. Maka dari itu: proposisi dari generasi ini “Man ‘Arafa Nafsahu, Faqad ‘Arafa Rabbahu.”
Penulis: Kowim Sabilillah (Tulungagung, 17 Juli 2022)
Editor: Munawir